Tribunners
Fenomena Hustle Culture: Antara Motivasi dan Burnout Generasi Muda
Fenomena hustle culture adalah cerminan dari ambisi generasi muda yang ingin meraih mimpi besar di tengah dunia yang penuh persaingan
Oleh: Tian Rahmat, S.Fil. - Alumnus Filsafat IFTK Ledalero, Flores/Pemerhati Isu-isu Strategis
HUSTLE culture, sebuah istilah yang menggema di kalangan generasi muda, sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan gairah dan dorongan untuk meraih impian. Namun di sisi lain, ia juga membawa generasi muda ke jurang burnout yang menguras fisik dan mental. Fenomena ini telah menjadi simbol gaya hidup modern yang terjebak antara motivasi berlebih dan kehancuran diri yang perlahan.
Hustle Culture: Definisi dan realitas
Istilah hustle culture mengacu pada paradigma kerja keras yang tiada henti, di mana keberhasilan sering kali diukur dari jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja atau produktivitas tanpa jeda. Erin Griffith mendeskripsikan budaya ini sebagai “obsesi untuk bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih cepat daripada orang lain demi mengejar mimpi kesuksesan.” The New York Times (2021)
Di era digital, media sosial menjadi panggung utama yang mengilustrasikan betapa hebatnya hustle culture. Kita melihat para influencer memamerkan rutinitas kerja 16 jam sehari, mengklaim bahwa tidur adalah kemewahan, dan membentuk narasi bahwa kesuksesan adalah hasil dari kelelahan yang konstan.
Namun, hemat saya apakah semua ini sepadan? Menurut Christina Maslach, seorang profesor psikologi dari University of California yang juga penulis Burnout: The Cost of Caring (1982), “Kelelahan kronis akibat tekanan kerja tidak hanya merusak produktivitas, tetapi juga kesehatan mental dan hubungan sosial.”
Generasi muda dan godaan hustle culture
Generasi muda, terutama generasi milenial dan gen Z, adalah kelompok yang paling rentan terhadap godaan hustle culture. Mereka dibesarkan dalam dunia yang mendewakan kesuksesan individu dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pekerjaan dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Dalam survei yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2023, ditemukan bahwa 48 persen dari generasi milenial merasa bahwa mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka, bahkan setelah jam kerja selesai. Hal ini diperparah dengan fenomena toxic productivity, di mana seseorang merasa bersalah jika tidak terus-menerus produktif.
Mengutip Mark Manson dalam bukunya The Subtle Art of Not Giving a F** (2016)*, “Ketika kita mengukur nilai diri berdasarkan pencapaian semata, kita menciptakan pola pikir yang berbahaya dan menghancurkan.” Pola pikir inilah hemat saya yang sering menjebak generasi muda dalam spiral yang tak berujung.
Motivasi atau eksploitasi?
Pendukung hustle culture sering kali berargumen bahwa bekerja keras adalah kunci kesuksesan. Tokoh seperti Elon Musk, yang dikenal dengan etos kerjanya yang luar biasa, sering kali dijadikan panutan. Musk pernah berujar, “Kerahkan tenaga hingga 80 hingga 100 jam setiap pekan, sebab tanpa itu, langkahmu akan tertinggal dari mereka yang lebih gigih. Jika Anda tidak melakukannya, seseorang akan mengalahkan Anda.”
Namun, di balik narasi itu, muncul pertanyaan penting: Apakah hustle culture benar-benar memotivasi, atau justru mengeksploitasi? Dalam artikel yang diterbitkan di Harvard Business Review (2019), Rahaf Harfoush menyoroti bahwa hustle culture sering kali digunakan oleh perusahaan untuk mengeksploitasi tenaga kerja muda dengan dalih “passion” dan “dedikasi.”
Harfoush menambahkan bahwa budaya ini menciptakan standar yang tidak realistis, yang akhirnya membebani individu dengan tekanan yang tak tertahankan. “Ketika orang dipaksa untuk terus bekerja tanpa istirahat, mereka tidak hanya kehilangan produktivitas, tetapi juga kehilangan jati diri mereka,” tulisnya.
Burnout: Harga yang harus dibayar
Kelelahan jiwa atau burnout menjelma sebagai bayang-bayang tak terelakkan dari kerasnya arus budaya hustle. Dalam buku The Burnout Epidemic (2021), Jennifer Moss menjelaskan bahwa burnout bukan hanya kelelahan biasa, tetapi juga mencakup perasaan sinisme, ketidakberdayaan, dan hilangnya makna hidup.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan telah mengklasifikasikan burnout sebagai fenomena pekerjaan dalam International Classification of Diseases (ICD-11) pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dampak hustle culture tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebuah studi dari American Psychological Association (2022) menemukan bahwa 79 persen pekerja milenial mengalami gejala burnout, termasuk insomnia, kecemasan, dan depresi. Fakta ini menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk budaya kerja keras yang berlebihan.
Mencari jalan tengah
Hustle culture bukanlah musuh yang harus dihancurkan sepenuhnya, tetapi ia perlu didekati dengan bijaksana. Generasi muda harus belajar membedakan antara motivasi yang sehat dan ekspektasi yang merusak.
Cal Newport, penulis Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World (2016), menyarankan bahwa produktivitas sejati hanya dapat dicapai dengan fokus yang mendalam dan waktu istirahat yang cukup. ”Kita tak mungkin terus-menerus menekan diri bekerja tanpa membayar mahal dengan terkikisnya ketenangan jiwa dan pikiran.” tulisnya.
Selain itu, perusahaan dan organisasi juga harus mengambil tanggung jawab untuk menciptakan budaya kerja yang lebih sehat. Model kerja yang fleksibel, penghargaan terhadap waktu istirahat, dan program kesejahteraan karyawan dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif hustle culture.
Kesimpulan
Fenomena hustle culture adalah cerminan dari ambisi generasi muda yang ingin meraih mimpi besar di tengah dunia yang penuh persaingan. Namun, ambisi ini harus diarahkan dengan bijak agar tidak berubah menjadi bumerang yang menghancurkan.
Sebagaimana kata Aristoteles, “Kebahagiaan adalah hasil dari tindakan yang seimbang.” Generasi muda harus belajar bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari seberapa keras mereka bekerja, tetapi juga dari seberapa baik mereka menjaga keseimbangan hidup.
Mari kita jadikan fenomena hustle culture sebagai pelajaran berharga untuk menciptakan dunia kerja yang lebih manusiawi, di mana motivasi dan kesejahteraan berjalan seiring. Hanya dengan cara ini, hemat saya kita dapat memastikan bahwa ambisi tidak berubah menjadi kelelahan yang tak berujung. (*)
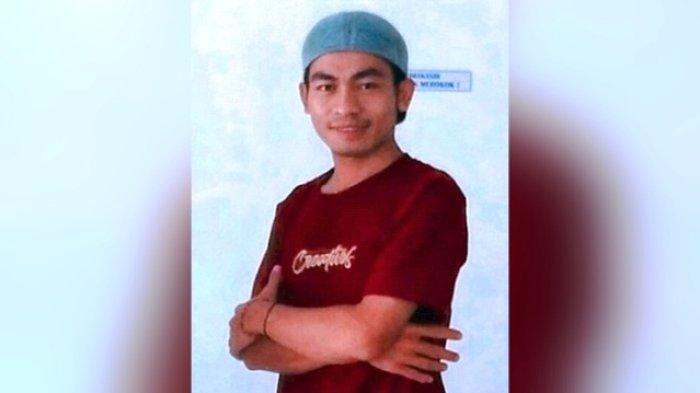













![[FULL] Meski Koordinator Aksi Damai & Demo Jilid II Batal, Pakar: Sulit Warga Maafkan Bupati Pati](https://img.youtube.com/vi/0qdqol4f7aU/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.