Tribunners
Dinasti Kurikulum yang Tak Pernah Monarki
Kurikulum harus dibangun atas dasar riset mendalam, kolaborasi dengan guru dan akademisi, serta evaluasi yang transparan.
Oleh: Firdaus - Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
DALAM sejarah pendidikan Indonesia, kurikulum telah silih berganti dengan semangat perubahan, namun tetap meninggalkan jejak yang nyaris seragam: kebingungan. Setiap pergantian menteri atau era pemerintahan seolah melahirkan "dinasti" baru dalam dunia pendidikan. Dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka dan sebentar lagi kemungkinan akan berganti pula.
Metamorfosis yang terjadi menunjukkan wajahnya berubah, namanya berganti, tetapi substansi kegamangan di lapangan nyaris tetap. Hal ini selalu kita (para pendidik) hadapi setiap kali ada pergantian kekuasaan yang kemudian memberikan gaung yang samar untuk menentukan arah kompas pendidikan bangsa.
Yang menarik, meski disebut sebagai "dinasti", kurikulum Indonesia tak pernah benar-benar monarki. Ia tidak memiliki satu "raja" yang visioner dan konsisten. Alih-alih berdiri kokoh di atas pilar filosofi pendidikan jangka panjang, kurikulum kita kerap lahir dari kepentingan sesaat, program lima tahunan, atau sekadar rebranding politik.
Kurikulum sebagai alat politik?
Perubahan kurikulum di Indonesia sering kali tidak bisa dilepaskan dari pergantian menteri pendidikan atau presiden. Setiap tokoh yang memimpin kementerian merasa perlu meninggalkan “jejak sejarah” melalui kurikulum baru. Dalam hal ini, kurikulum menjadi alat politik pencitraan, bukan instrumen pedagogis yang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Padahal, pendidikan adalah proses jangka panjang yang memerlukan kestabilan arah dan visi.
Tidak seperti monarki, yang cenderung mempertahankan garis keturunan dan sistem pemerintahan yang stabil, perubahan kurikulum di Indonesia justru fluktuatif dan reaktif. Ia seperti rezim demokratis yang terlalu cair: mengikuti arus, mudah berubah, dan sering tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Inilah ironi dari "dinasti" yang tak pernah benar-benar monarki selalu berganti tampuk kepemimpinan tanpa kesinambungan visi.
Lebih dari itu, perubahan kurikulum tidak selalu berdasarkan evaluasi ilmiah atau refleksi mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ia kerap didasarkan pada persepsi elite pendidikan dan birokrasi, yang belum tentu sesuai dengan kenyataan di kelas-kelas pelosok negeri.
Sementara itu, perubahan kurikulum yang terjadi jika ada pergantian kekuasaan seakan-akan ada tuntutan bagi menteri atau presiden yang terpilih untuk mengeluarkan produk baru yang tampak terlihat beda, tetapi masih memiliki esensi yang tetap sama, atau yang sering kita dengar dengan istilah “ganti baju”.
Di sisi lain, tuntutan perubahan kurikulum harus dieksekusi karena menyangkut serapan anggaran kementerian yang harus direalisasikan dalam berbagai bentuk proyek kementerian, salah satunya adalah perubahan kurikulum yang diawali dengan wacana yang kemudian dilakukan perencanaan, lalu disahkan dan sosialisasikan, selanjutnya diaplikasikan ke setiap satuan pendidikan. Proses tersebut yang dimulai dari hilir sampai ke hulu, tentunya dianggap efektif dalam penyerapan anggaran kementerian yang dalam pengadaannya menjadi proyek kementerian yang rentan dikorupsi.
Guru dan siswa sebagai korban eksperimen
Guru dan siswa menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan kurikulum. Ketika kurikulum berubah, guru dituntut menyesuaikan metode, pendekatan, hingga administrasi pengajaran. Namun, pelatihan yang diberikan sering kali bersifat seremonial, tidak mendalam, dan tidak menjawab kebutuhan spesifik di lapangan. Banyak guru yang mengaku bingung, bahkan stres, dengan tumpukan administrasi baru yang dibawa oleh kurikulum baru.
Di satu sisi, guru dituntut menjadi fasilitator, pembimbing, bahkan inovator dalam pembelajaran. Tetapi di sisi lain, mereka juga dibebani dengan laporan-laporan administratif yang menguras energi dan waktu. Ketimpangan kompetensi guru di berbagai daerah membuat implementasi kurikulum tidak merata.
Sementara itu, siswa menjadi korban dari ketidakkonsistenan sistem. Mereka harus mengikuti sistem penilaian yang terus berubah, beban pelajaran yang kadang terlalu banyak atau justru terlalu minim, serta metode belajar yang belum tentu sesuai dengan karakteristik mereka.
Sekolah-sekolah di daerah tertinggal makin tertinggal karena tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi dengan cepat. Anak-anak di kota mendapatkan pelatihan coding dan literasi digital, sedangkan di desa, buku teks pun masih menjadi barang langka.


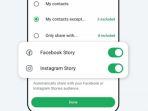

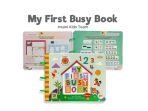







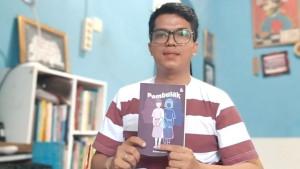

![[FULL] Demo Buruh Kepung Senayan, Said Iqbal: DPR Parah, RUU Setahun Panja Doang, Kasihan Presiden](https://img.youtube.com/vi/TGRtOGQV2Z4/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.