Tribunners
Guru Dalam Disrupsi Moral Digital dan Tergerusnya Otoritas Pendidikan Oleh Budaya Media Sosial
Guru yang menjadi sumber utama nilai, ilmu, dan keteladanan kini bersaing dengan influencer, kreator konten, dan algoritma media sosial
Penulis Muhammad Isnaini
(Dosen Pengembangan Media dan Sumber Belajar UIN Raden Fatah Palembang)
Era digital menghadirkan perubahan besar dalam struktur otoritas moral dan pengetahuan di ruang pendidikan.
Guru yang selama ini menjadi sumber utama nilai, ilmu, dan keteladanan kini harus bersaing dengan figur baru yang muncul dari ruang maya para influencer, kreator konten, dan algoritma media sosial yang lebih sering dipercaya siswa.
Fenomena ini menandai terjadinya disrupsi moral digital, yakni pergeseran otoritas moral dan epistemik dari institusi pendidikan formal ke ruang digital yang diatur oleh logika viralitas dan popularitas (Turkle, 2011).
Dan era digital tidak hanya mengubah cara siswa memperoleh informasi, tetapi juga bagaimana mereka membentuk persepsi tentang kebenaran dan otoritas.
Dalam konteks budaya digital, keabsahan suatu pengetahuan tidak lagi ditentukan oleh sumber akademik atau otoritas formal seperti guru, melainkan oleh seberapa besar konten tersebut mendapat pengakuan sosial melalui likes, shares, atau komentar positif (Couldry, 2012).
Hal ini menciptakan bentuk baru dari epistemic authority, di mana popularitas menggantikan kompetensi sebagai tolok ukur kebenaran. Akibatnya, guru kehilangan posisi simbolik sebagai figur otoritatif dalam membentuk horizon moral dan intelektual siswa, karena dunia digital menawarkan otoritas alternatif yang tampak lebih dekat, cepat, dan menyenangkan.
Fenomena ini memperlihatkan pergeseran nilai dari culture of discipline menuju culture of entertainment. Seperti dijelaskan oleh Postman (1985) dalam Amusing Ourselves to Death, masyarakat modern cenderung menilai segala hal berdasarkan daya hiburnya, bukan kedalaman isinya.
Ketika logika hiburan mendominasi ruang belajar digital, pendidikan moral yang bersifat reflektif dan menuntut kesabaran menjadi kurang diminati.
Guru, yang mengajarkan nilai melalui proses dan keteladanan, kini menghadapi generasi yang dibentuk oleh algoritma kepuasan instan. Inilah bentuk paling nyata dari disrupsi moral digital di mana makna digantikan oleh sensasi, dan kebijaksanaan digantikan oleh viralitas.
Pergeseran Otoritas dalam Ekosistem Digital
Sistem pendidikan tradisional, seperti guru memiliki legitimasi moral dan intelektual yang diakui secara sosial. Namun kini, kekuasaan simbolik tersebut mulai memudar.
Masyarakat jaringan (network society) membentuk sistem sosial baru di mana sumber otoritas tidak lagi bergantung pada posisi institusional, melainkan pada kemampuan mengelola arus informasi.
Dalam konteks ini, siswa lebih banyak mengonsumsi dan mempercayai informasi dari media sosial, yang seringkali dikemas dengan gaya menarik dan emosional, dibandingkan penjelasan rasional guru di ruang kelas.
Budaya media sosial juga menumbuhkan digital tribalism, yaitu kecenderungan anak muda membentuk komunitas nilai berdasarkan minat digital bersama, bukan lagi nilai-nilai moral yang diwariskan melalui pendidikan formal (Jenkins, 2016).
Akibatnya, orientasi moral siswa bergeser dari ketaatan pada norma menjadi kesetiaan pada figur digital yang dianggap “relatable”.
Perubahan lanskap sosial ini memperlihatkan bahwa legitimasi moral dan intelektual kini tidak lagi bersumber dari status profesional, melainkan dari performativitas digital kemampuan seseorang menampilkan diri secara menarik dan persuasif di dunia maya (Goffman, 1959; boyd, 2014).
Para influencer dan kreator konten dengan cepat merebut perhatian siswa karena mereka mampu menghadirkan pesan yang singkat, emosional, dan mudah dipahami.
Di sisi lain, gaya komunikasi guru yang masih berorientasi pada model instruksional satu arah sering kali dianggap kaku dan kurang relevan dengan konteks kehidupan digital siswa. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gaya komunikasi antargenerasi, di mana otoritas berbasis substansi kalah oleh otoritas berbasis narasi dan estetika digital.
Selain itu, media sosial menciptakan ruang interaksi semu yang memberikan ilusi kedekatan antarasiswa dan tokoh digital.
Dalam ruang ini, figur-figur populer tampil bukan sebagai otoritas moral yang menasihati, tetapi sebagai teman sebaya yang “memahami” perasaan dan kegelisahan pengikutnya.
Seperti dikemukakan oleh Thompson (2005), media modern membentuk bentuk baru dari hubungan para sosial, di mana khalayak merasa memiliki koneksi emosional dengan tokoh publik yang sebenarnya tidak mereka kenal secara personal.
Relasi semacam ini membuat pesan dari guru sering kali terasa jauh dan formal, sementara pesan dari influencer tampak hangat dan otentik, meskipun sering kali dangkal secara substansi.
Fenomena digital tribalism di atas memperkuat pergeseran ini dengan menciptakan ruang nilai yang terfragmentasi. Siswa kini lebih terikat pada identitas digital kelompoknya entah itu komunitas penggemar, forum gim, atau grup media sosial tertentu yang membentuk sistem moral dan bahasa sendiri.
Nilai kebersamaan dan solidaritas yang dulu dibangun melalui sekolah kini bergeser menjadi solidaritas virtual yang berbasis algoritma kesamaan minat (Jenkins, 2016).
Dalam situasi seperti ini, peran guru tidak hanya terancam secara fungsional, tetapi juga secara kultural. Guru menghadapi tantangan untuk tidak sekadar mentransfer ilmu, melainkan juga merebut kembali ruang moral yang kini diisi oleh budaya digital dengan menawarkan kehadiran yang relevan, reflektif, dan bermakna bagi generasi yang hidup di bawah dominasi algoritma.
Ketika Algoritma Menggantikan Nasihat
Fenomena ini semakin kompleks karena algoritma media sosial bekerja dengan prinsi pengagement-based system, yakni menampilkan konten yang paling sering diklik, disukai, atau dibagikan.
Bagi generasi Z, sistem ini menciptakan realitas moral baru yang ditentukan bukan oleh kebenaran, melainkan oleh popularitas (Pariser, 2011). Dengan demikian, pesan pendidikan guru yang berbasis nilai, proses, dan kedisiplinan kerap kalah oleh konten instan yang memberi kepuasane mosional cepat.
Menurut disiplin dan konteks psikologi pendidikan, kondisi ini berkaitan erat dengan teori reinforcementdari B.F. Skinner (1953), di mana perilaku manusia cenderung terbentuk oleh pola penguatan yang berulang.
Media sosial, melalui sistem likes dan komentar positif, secara tidak sadar memperkuat perilaku konsumtif terhadap konten yang menyenangkan, bukan yang bermakna.
Generasi Z yang tumbuh di lingkungan digital mengalami dopamine loop siklus kepuasan sesaat yang terus diperbarui oleh interaksi daring. Hal ini menjadikan nilai-nilai seperti kesabaran, tanggungjawab, dan integritas yang diajarkan guru melalui proses panjang tampak membosankan dan tidak relevan. Maka, bukan hanya otoritas guru yang tergerus, tetapi juga daya tahan moral siswa terhadap distraksi digital semakin melemah.
Sistem algoritmik ini tidak netral. Ia memiliki agenda ekonomi dan ideologis yang menempatkan perhatian pengguna sebagai komoditas utama (attention economy) (Hassan, 2020).
Dengan menonjolkan konten yang memicu emosi, algoritma mempersempit ruang bagi refleksi moral yang tenang dan mendalam. Akibatnya, siswa hidup dalam echo chamber, di mana mereka hanya terpapar pandangan yang memperkuat keyakinan dan selera pribadi, tanpa pernah mengalami perdebatan nilai yang sehat.
Dalam kondisi demikian, tugas guru bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menuntun siswa keluar dari jebakan algoritmik dengan menumbuhkan kesadaran kritis dan etika digital. Inilah tantangan baru bagi pendidikan moral di era digital, bagaimana menanamkan nilai dalam dunia yang diatur bukan oleh guru, melainkan oleh kode dan data.
Secara psikologis, generasi digital ini hidup dalam budaya attention economy, di mana perhatian menjadi komoditas utama (Hassan, 2020). Akibatnya, pesan moral guru sering dianggap “kurangmenarik” dibandingkan hiburan yang dikemas dengan visual dinamis, humor, atau narasi personal.
Di sinilah otoritas moral guru terdisrupsi bukan karena mereka kehilangan nilai, tetapi karena cara mereka berkomunikasi tidak sesuai dengan pola perhatian digital siswa.
Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif teoriuses and gratifications (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1974), yang menyatakan bahwa individu secara aktif memilih media yang mampu memenuhi kebutuhan psikologis dan sosialnya.
Bagi generasi digital, media sosial bukan sekadar sarana informasi, tetapi juga ruang identitas, ekspresi diri, dan validasi sosial. Karena itu, mereka lebih tertarik pada pesan yang memberikan resonansi emosional dan keterlibatan personal dibandingkan dengan pesan moral yang normatif.
Guru yang masih menggunakan pendekatan konvensional sering gagal menyesuaikan diri dengan dinamika ini. Maka, agar pesan moral dapat diterima, guru perlu mengadaptasi strategi komunikasinya dengan menggabungkan pendekatan naratif, visual, dan empatik bukan hanya menyampaikan nilai, tetapi juga menghadirkan nilai tersebut dalam bentuk yang komunikatif, autentik, dan relevan dengan dunia digital siswa.
Krisis Kompetensi Literasi Digital Guru
Salah satu akar persoalan terletak pada kesenjangan literasi digital antara guru dan siswa.
Menurut Buckingham (2013), media literacy bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan media, tetapi kemampuan kritis dalam memahami bagaimana media membentuk makna, nilai, dan identitas.
Sayangnya, banyak guru di Indonesia masih memandang media sosial sebatas hiburan atau ancaman, bukan ruang pembelajaran moral baru. Padahal, generasi Z memandang dunia digital sebagai perpanjangan diri mereka sendiri.
Ketika guru tidak hadir di ruang digital, maka ruang itu akan diisi oleh figur lain yang tidak selalu membawa nilai edukatif. Oleh karena itu, pelatihan guru perlu bergeser dari sekadar digital skills ke arah digital communication ethics dan digital pedagogy, agar pesan moral dapat disampaikan dengan bahasa dan gaya yang sesuai dengan ekosistem budaya digital siswa.
Kesenjangan literasi digital antara guru dan siswa tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga bersifat kultural dan epistemologis.
Generasi guru yang tumbuh di era pra-digital terbiasa dengan pola berpikir linear, hierarkis, dan berbasis otoritas formal, sedangkan generasi Z hidup dalam dunia yang bersifat decentralized dan participatory (Jenkins, 2009).
Mereka membangun makna melalui interaksi, kolaborasi, dan pengalaman visual yang intens. Akibatnya, metode pembelajaran yang berpusat pada guru sering kali tidak sejalan dengan cara berpikir siswa digital yang lebih horizontal dan interaktif.
Jika guru tidak memahami logika budaya digital ini, maka ia akan kesulitan menanamkan nilai moral karena menggunakan bahasa yang tidak lagi “beresonansi” dengan dunia simbolik siswa.
Selain itu, keterlambatan adaptasi guru terhadap perkembangan media digital juga disebabkan oleh minimnya dukungan kelembagaan dan kebijakan pendidikan yang berpihak pada penguatan kompetensi digital guru.
Program pelatihan yang ada umumnya masih menekankan aspek administrative seperti penggunaan platform e-learning atau aplikasi ujian daring tanpa menyentuh dimensietis dan pedagogis dari komunikasi digital. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Rheingold (2012), digital literacy sejati menuntut kemampuan berpikir kritis, etis, dan kolaboratif dalam ruang siber.
Dengan membekali guru pada tiga aspek tersebut etika, empati, dan ekspresi digital, maka guru dapat menjadi mediator moral yang relevan di tengah budaya algoritmik, bukan sekadar pengguna pasif teknologi.
Reposisi Peran Guru dalam Budaya Digital
Pada konteks disrupsi moral digital ini, guru tidak bisa lagi hanya menjadi penyampai ilmu, tetapi harus bertransformasi menjadi digital mentor pembimbing nilai dan makna di tengah banjir informasi.
Teori konstruktivismesosial (Vygotsky, 1978) menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan budaya, dengan demikian ruang digital justru dapat menjadi wahana pembentukan nilai jika guru mampu hadir secara bermakna di dalamnya.
Guru juga perlu menegaskan kembali ethos profesionalnya sebagai penjaga nalar kritis dan empati moral. Seperti dikatakan Freire (1970), pendidikan sejatinya adalah praktik pembebasan, bukan indoktrinasi.
Dalam era digital, pembebasan itu berarti menuntun siswa untuk tidak menjadi budak algoritma, melainkan subjek moral yang sadar akan nilai, makna, dan tanggungjawab sosialnya di ruang maya.
Mewujudkan peran sebagai digital mentor, guru perlu mengintegrasikan pendekatan pedagogi reflektif dan humanistik dalam aktivitas digitalnya.
Menurut Mezirow (1991), pembelajaran yang transformatif terjadi ketika individu diajak merefleksikan asumsi dan pengalaman mereka secara kritis untuk membentuk pemahaman baru yang lebih bermakna.
Dalam konteks ini, guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran kognitif, tetapi juga penuntun refleksi moral di tengah kompleksitas informasi digital.
Dengan memanfaatkan media sosial atau platform digital secara bijak, misalnya melalui diskusi etika daring, proyek kolaboratif berbasis nilai, atau konten edukatif yang inspiratif guru dapat menanamkan kesadaran moral yang relevan dengan dunia siswa.
Dengan demikian, ruang digital bukan lagi ancaman bagi pendidikan, melainkan menjadi laboratorium moral baru tempat nilai, nalar, dan empati dapat tumbuh dalam format yang sesuai dengan zaman.
Penutup
Disrupsi moral digital bukan akhir dari otoritas guru, tetapi panggilan untuk bertransformasi. Guru masa kini ditantang untuk tidak hanya menguasai ilmu dan teknologi, tetapi juga menjadi narator moral di tengah banjir informasi.
Dunia digital memang telah mengubah cara siswa belajar dan mencari panutan, namun peran guru tetap esensial sebagai penjaga nurani di tengah kebisingan algoritma.
Seperti ditegaskan oleh Noddings (2013), inti pendidikan adalah care atau kepedulian. Dan kepedulian itu tidak bisa digantikan oleh influencer mana pun, karena ia lahir dari relasi manusiawi yang tulus, yang menjadi jiwa sejati dari profesi guru.
Transformasiperan guru di era disrupsi moral digital juga menuntut keberanian untuk menegosiasikan kembali makna pendidikan itu sendiri.
Pendidikan tidak lagi cukup dimaknai sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses meaning making membangun makna hidup di tengah kompleksitas dunia digital (Biesta, 2015).
Tugas guru bukan hanya mengajarkan apa yang benar, tetapi juga membantu siswa memahami mengapa sesuatu bernilai benar dalam konteks kemanusiaan dan kebersamaan.
Dengan demikian, otoritas guru di masa depan tidak akan diukur dari seberapa banyak informasi yang ia miliki, tetapi dari seberapa dalam ia mampu menyentuh hati dan menuntun kesadaran moral generasi digital.


















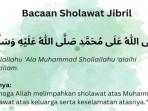

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.