Tribunners
Sumpah Pemuda dan Spirit Kebersamaan Melayu Nusantara
Sumpah Pemuda bukan sekadar kenangan sejarah, melainkan janji moral yang harus terus diperbarui di setiap zaman
Oleh: Estu Widiyowati - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
KETIKA 28 Oktober kembali datang, bangsa ini seperti diingatkan oleh gema dari masa lampau– suara para pemuda 1928 yang memproklamasikan diri sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Namun, di balik baris–baris sumpah itu, ada sesuatu yang lebih mendalam dari sekadar janji kebangsaan, yakni sebuah spirit kebersamaan yang berakar dalam kebudayaan Melayu Nusantara, kebersamaan yang bukan dibangun dari keseragaman, melainkan dari semangat persaudaraan dalam keberagaman.
Sumpah Pemuda lahir bukan di ruang hampa sejarah. Ia tumbuh dari pergulatan panjang antara kolonialisme dan kesadaran identitas. Di bawah bayang–bayang penjajahan, para pemuda Nusantara menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata atau kekuasaan, melainkan pada kesanggupan untuk menyingkirkan ego kedaerahan dan menjahitnya menjadi tenunan persaudaraan. Di situlah akar kebudayaan Melayu bekerja, dalam bentuk gotong royong, musyawarah, dan rasa sepenanggungan.
Kita sering membaca Sumpah Pemuda sebagai dokumen politik, padahal ia juga adalah teks kultural. Ia bukan sekadar pernyataan politik kebangsaan, tetapi juga cerminan etika sosial Melayu, “Bersatu bukan menyeragamkan, melainkan untuk saling meneguhkan.” Dalam logika kebersamaan Melayu, identitas tidak meniadakan yang lain, melainkan memberi ruang bagi yang berbeda untuk tetap hadir.
Kebersamaan yang terlupakan
Ironisnya, setelah hampir satu abad berlalu, semangat kebersamaan itu mulai memudar. Di era digital kini, kita menyaksikan bangsa yang justru terpecah oleh politik identitas, oleh ujaran kebencian yang menyusup melalui algoritma media sosial, oleh egoisme kelompok yang menjadikan “perbedaan” sebagai senjata. Jika Sumpah Pemuda adalah ikrar untuk bersatu, maka hari ini kita seakan terperangkap dalam “sumpah baru” yang tak terucap –sumpah yang mencurigai, menyingkirkan, bahkan membenci sesama anak bangsa.
Fenomena itu menunjukkan betapa kebersamaan bukan sesuatu yang sekali jadi. Ia harus terus dirawat, dipelihara, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari – hari. Di sinilah kita kembali pada kebijaksanaan Melayu, “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” Ungkapan itu bukan hanya pepatah lama, melainkan cara hidup yang menempatkan solidaritas sebagai fondasi peradaban.
Namun, dalam sistem sosial modern yang makin individualistik, nilai–nilai semacam itu sering dianggap kuno. Padahal, bangsa ini dibangun bukan di atas fondasi kompetisi, melainkan kolaborasi. Ketika semangat gotong royong melemah, maka yang tersisa hanyalah masyarakat yang rapuh, mudah diadu, mudah dipecah, dan mudah diarahkan oleh kepentingan politik sesaat.
Refleksi politik kebersamaan
Jika kita meminjam kacamata analisis budaya politik, Sumpah Pemuda dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap hegemoni kolonial yang sengaja menanamkan politik pecah belah. Para pemuda waktu itu memahami bahwa penjajahan bukan hanya penaklukan fisik, tetapi juga penaklukan batin, membuat sesama anak bangsa saling curiga dan merasa lebih tinggi dari yang lain.
Kini, ancaman itu datang bukan dari kolonialisme klasik, melainkan dari “kolonialisme baru” yang bekerja melalui ekonomi, teknologi, dan informasi. Media sosial, misalnya, menajdi arena baru di mana “kolonialisme algoritma” menciptakan segregasi digital –setiap orang hidup dalam gelembung informasi yang memperkuat prasangka dan mempersempit empati.
Dalam situasi itu , semangat kebersamaan yang diwariskan oleh Sumpah Pemuda menjadi makin relevan, ia menuntut kita untuk melampaui sekat–sekat buatan mesin dan ideologi dan kembali menegaskan kemanusiaan sebagai titik temu.
Di sinilah kita perlu membaca ulang warisan budaya Melayu sebagai fondasi etis kebangsaan. Dalam pandangan dunia Melayu, politik tidak semata urusan kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral. Kekuasaan yang kehilangan moralitas akan melahirkan kekerasan simbolik dan sosial, sebagaimana terlihat dalam banyak konflik horizontal di negeri ini. Oleh karena itu, semangat Sumpah Pemuda seharusnya tidak hanya diperingati, tetapi juga dihidupi sebagai etika politik –politik yang berakar pada kasih sayang, bukan kebencian; pada dialog, bukan dominasi.
Kebudayaan Melayu sebagai etika sosial
Kebudayaan Melayu menyimpan pandangan yang unik tentang hubungan manusia dan komunitas. Dalam tradisi Melayu, seseorang baru dianggap “ada” jika ia hadir bersama orang lain. “Aku” tidak memiliki makna di luar “kita”. Inilah konsep kolektivitas yang menjiwai seluruh struktur sosial Nusantara sebelum datangnya modernitas.
Ketika Sumpah Pemuda menegaskan satu bangsa dan satu bahasa, ia tidak meniadakan identitas lokal, melainkan merangkulnya dalam kerangka kesetaraan. Bahasa Indonesia, misalnya, dipilih bukan karena ia paling dominan, tetapi karena ia paling inklusif, mudah diterima oleh berbagai suku dan daerah. Pilihan itu bukan keputusan politik semata, melainkan keputusan kultural yang mencerminkan kebijaksanaan Melayu, mencari titik temu di tengah perbedaan.
Spirit inilah yang seharusnya menjadi dasar pembangunan bangsa hari ini. Namun sayangnya, kebijakan publik dan politik identitas kerap berjalan ke arah sebaliknya, menonjolkan perbedaan, bukan mempertemukan. Padahal, dalam logika kebersamaan Melayu, harmoni tidak lahir dari penyeragaman, tetapi dari kesediaan untuk berbagi ruang, rasa, dan makna.
Refleksi moral: menjadi bangsa yang beradab
Sumpah Pemuda bukan sekadar dokumen sejarah, ia adalah cermin moral yang menuntun kita untuk menjadi bangsa yang beradab. Dalam konteks kebangsaan hari ini, beradab berarti mampu menahan diri di tengah provokasi, menghormati perbedaan pendapat, dan memuliakan kemanusiaan di atas kepentingan politik.
Kita hidup di masa di mana teknologi telah memperpendek jarak, tetapi sekaligus memperlebar jurang batin antarwarga. Dalam situasi semacam ini, kebersamaan tidak lagi cukup hanya diucapkan, ia harus dihidupi melalui tindakan nyata, dari cara kita berinteraksi di media sosial, memilih kata, hingga memperlakukan yang lemah.
Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa bangsa ini lahir bukan dari kekuatan satu etnis, agama, atau wilayah, tetapi dari keikhlasan untuk berbagi nasib dan masa depan. Kebersamaan Melayu Nusantara adalah warisan yang memberi kita daya tahan kultural luar biasa, dari Aceh hingga Papua, dari Melayu Riau hingga Bugis, semua terikat oleh semangat “serumpun sejiwa”.
Kini, tugas generasi kita adlaah memastikan bahwa semangat itu tidak membeku menjadi slogan, tetapi berdenyut dalam tindakan, dalam kebijakan yang adil, dalam ruang publik yang terbuka, dan dalam media sosial yang beretika. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang seragam, melainkan bangsa yang mampu menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan moral.
Meneruskan ikran pemuda 1928
Ketika para pemuda 1928 mengucapkan sumpahnya, mereka sedang memaknai ulang arti “kita”. Mereka sedang menolak narasi kolonial yang memecah, dan menggantinya dengan narasi kebersamaan yang meneguhkan.
Hari ini, tugas kita adalah meneruskan ikrar itu, bukan hanya dalam upacara, tetapi dalam kesadaran. Spirit kebersamaan Melayu Nusantara menuntun kita untuk melihat Indonesia bukan sebagai sekumpulan individu yang bersaing, melainkan sebagai keluarga besar yang saling menjaga.
Sumpah Pemuda bukan sekadar kenangan sejarah, melainkan janji moral yang harus terus diperbarui di setiap zaman, bahwa di tengah segala perbedaan, kita tetap satu – dalam rasa, dalam jiwa, dan dalam cinta kepada tanah air. (*)















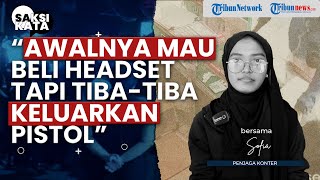





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.