Tribunners
Pilkada Hasilkan Apa?
Tahun 2005 menjadi tahun awal sejarah dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang disebut pemilukada secara langsung
Oleh: Ariandi A Zulkarnain, S.IP, M.Si., C.M.C - Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
SEJAK beranjak dari reformasi upaya penguatan dan pendalaman demokrasi terus dilakukan dalam rangka mencapai tatanan demokrasi yang makin matang dan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Pemilihan umum menjadi salah satu sarana penting dalam rangka menciptakan transisi dan sirkulasi elite secara damai, demokratis, dan berkesinambungan.
Pemilihan umum menjadi jalan mengartikulasikan representasi politik dalam panggung masyarakat yang multikultural di Indonesia, dengan jumlah penduduk Indonesia 282,4 juta jiwa dengan penduduk yang multietnik terdiri dari 1.340 suku bangsa, 6 agama, dan 245 aliran kepercayaan. Selain itu, kondisi demokrasi Indonesia hari ini ditopang dengan rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia berada pada kelas 2 sekolah menengah pertama (SMP) dan pendapatan penduduk Indonesia di bawah 6.000 USD.
Kondisi eksisting tersebut membuat pelaksanaannya mengalami tantangan dan kompleksitas sehingga upaya penyempurnaan perlu terus-menerus dilakukan. Secara prosedural dari masa ke masa, pemilu mulai menunjukkan peningkatan kualitas, namun masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pada praktik demokrasi substansial yang ditujukan untuk mencapai tujuan tujuan demokrasi yang dicita-citakan.
Tahun 2005 menjadi tahun awal sejarah dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang disebut pemilukada secara langsung, dilaksanakan di 7 Provinsi, 174 kabupaten, dan 32 kota dengan total keseluruhan 213 daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi penanda pilkada masuk pada rezim pemilu, dan DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang melaksanakan melalui undang-undang ini.
Hingga hari ini, kita sudah melakukan beberapa kali perubahan dan upaya penyempurnaan atas regulasi pilkada yang kemudian menjadi regulasi yang terpisah dengan undang-undang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mengalami beberapa kali penyempurnaan termasuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hingga berujung pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, setelah itu kita belum kembali memperbarui aturan main pemilihan kepala daerah tersebut.
Biaya Kontestasi yang Mahal
Sejak pertama kali pilkada dilakukan hingga saat ini (2005-2020) yakni sebanyak 1.825 kali pelaksanaan pilkada telah dihelat, masih terdapat beberapa persoalan pemilihan kepala daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ongkos kandidat yang mahal seolah-olah menjadi ekosistem yang masih sulit diubah, hal ini imbas dari politik mahar (sewa kendaraan/perahu) menjadi syarat yang diperlukan untuk memasuki wilayah kontestasi, selain jalur independen yang kecenderungannya masih menjadi jalan terjal bagi politisi untuk masuk ke dalam gelanggang dengan syarat yang tidak sederhana.
Ongkos yang mahal tersebut terdiri dari beberapa biaya politik dalam rangka menggerakkan mesin politik mulai dari biaya saksi TPS (uang transpor dan bimtek), biaya tim sukses (honor, sewa kantor/kendaraan, rapat, konsumsi dan operasional), biaya kampanye (iklan, alat peraga, rapat, dan perjalanan), beli suara (pemilih, tokoh masyarakat, dan panitia), serta biaya perselisihan pilkada (gugatan MK). Biaya-biaya tersebut merupakan konsekuensi dari budaya politik kita yang buruk sehingga aspek materiel (uang) yang dimaknai sebagai modal menjadi motor utama dalam menggerakkan mesin politik di akar rumput. Hal ini yang memperkuat posisi keterpautan politik (political linkage) bergerak dalam clientelistic linkage, yakni ikatan politik antara politisi dan pemilih yang didasarkan pada charisma personal dari politisi dan didasarkan pada insentif material tertentu dalam sebuah jaringan pertukaran langsung di antara keduanya.
Kondisi lain yang ikut memperkeruh ruang kontestasi terkait dengan sumber dana kandidat yang berasal dari kantong pribadi yang terbatas menjadi pintu masuk bagi cukong/investor politik mengambil kesempatan dan positioning. Hal ini juga diperkuat data dari KPK terdapat 82 persen pemilihan kepala daerah mendapat dukungan dana dari para cukong (pemilik modal) yang berdampak pada intervensi kekuasaan menjadi tidak terbatas. Galang dana yang dilakukan juga tidak maksimal dan terbatas sebagaimana diketahui sesuai dengan regulasi sumbangan perseorangan maksimal Rp75 juta dan sumbangan perusahaan maksimal Rp750 juta dan ditambah dengan sponsor dari parpol tidak berjalan dan kecenderungan parpol meminta jatah kepada kandidat.
Pecah Kongsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kondisi politik lokal juga memunculkan dinamika lain di dalamnya, salah satunya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memang sejak awal keterpautan politik tidak benar-benar muncul akibat akumulasi kepentingan publik, melainkan bentuk wujud dari pragmatisme elite politik dalam orientasi memenangkan kontestasi. Hal ini yang kemudian pada prosesnya di tengah jalan membuat pasangan kepala daerah tidak dalam visi yang sama dan berujung pecah kongsi.
Politisasi Birokrasi dan Netralitas ASN
Permasalahan lain ketika kontestasi calon kepala daerah diikuti oleh petahana, maka potensi politisasi birokrasi dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi persoalan mendasar di dalamnya. Hal ini tidak jauh dari persoalan yang belum diurai dari pejabat pembina kepegawaian yang idealnya terlepas dari kepentingan politik.
Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan pelanggaran atas netralitas ASN selalu mengalami peningkatan dari setiap perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Terakhir data tahun 2020 pada saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak diketahui terdapat 1.575 kasus, sedangkan informasi data KASN pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 2.034 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melanggar netralitas ASN.
Masih berkelindannya kepentingan yang muncul, tentu disebabkan karena beberapa hal mulai dari ikatan persaudaraan, ikatan kepentingan karier, kesamaan latar belakang, utang budi hingga tekanan dari pasangan calon yang berkontestasi. Hal ini tentu bermuara dari kedudukan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian yang menyebabkan ASN sulit bersikap netral.
Maraknya Politik Dinasti dan Kekerabatan
Pemilihan kepala daerah juga tidak lepas dari politik dinasti dan politik kekerabatan yang membuat ruang kontestasi tidak setara dan timpang bagi kandidat lain. Data CSIS, pada Pemilu 2024 ada 138 orang dari 580 caleg terpilih di DPR terafiliasi dinasti politik. Ada 87 orang anggota DPR terpilih yang berusia di bawah 40 tahun, 50 orang di antaranya terafiliasi dinasti politik. Demokrasi lokal menjadi dibajak oleh para elite (oligarki). Oligarki menjadi dominan ketika elite superkaya terlibat dalam kontestasi guna mempertahankan dan memperluas kekayaannya.
Data yang bisa dihimpun terjadi peningkatan dinasti politik dalam kontestasi pilkada pada 2014 di mana terdapat 11 persen kontestan terafiliasi dinasti politik, kemudian meningkat pada 2018 menjadi 21,5 persen, dan pada tahun 2020 menjadi 32 persen. Kemudian data dari Themis Law Firm menemukan 35 daerah dengan dinasti politik di pilkada serentak 2024. Dari 35 daerah ini, terdapat 42 figur politisi berlatar belakang keluarga politik yang maju di pilkada. Sebanyak 35 daerah tersebut terdiri atas 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota.
Kondisi itu membuat ruang kontestasi justru tidak terbuka secara demokratis, kaderisasi partai menjadi rusak karena terdapat upaya memprioritaskan ruang kandidasi pada basis kekerabatan. Hal ini memperkuat posisi ruang demokrasi menjadi elitis dan sulit dijangkau oleh kandidat di luar relasi kerabat. Selain itu, analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan politik dinasti dan politik kekerabatan berbahaya bagi demokrasi karena kooptasi kekuasaan oleh satu keluarga secara turun-temurun terkait erat dengan praktik korupsi. Imbas lainnya menyebabkan pertarungan gagasan menjadi berkurang dan mayoritas kandidat muncul dalam narasi populis.
Di tingkat lokal dalam pemilihan kepala daerah, pernah muncul narasi yang tegas dalam menata dan memitigasi makin suburnya dinasti politik di daerah, tetapi kemudian dibatalkan MK. Pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “kandidat tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati jeda satu kali masa jabatan”, kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terdapat klausul “tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan”, dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdapat pasal yang dibatalkan oleh MK yakni pasal yang menjelaskan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yakni tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Kemudian pada Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 hal ini kemudian tidak atur dengan pertimbangan kesetaraan hak untuk memilih dan dipilih yang menjadi basis rasional oleh Mahkamah Konstitusi.
Pemasukan kepala daerah yang minim menjadi pintu masuk korupsi? Tidak dimungkiri bahwa taya tarik kekuasaan adalah dekat dengan relasi kuasa dalam penataan dan distribusi alokasi sumber daya. Aspek pendapatan materiel yang bisa didapatkan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah sumber pemasukan kepala daerah. Jika diperhatikan secara faktual terdapat beberapa sumber pendapatan yang bisa kita analisis yakni dimulai dari gaji/tunjangan jabatan kepala daerah.
Merujuk pada pendapatan terakhir kepala daerah gubernur mendapatkan gaji Rp8.400.000 dan wali kota/bupati mendapatkan gaji Rp5.880.000. Dengan gaji yang cenderung kecil dan otoritas yang besar, beberapa penyelewengan kewenangan terjadi di beberapa tempat dengan modus penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa (infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain), penyalahgunaan perizinan, penyalahgunaan APBD/kas daerah (modus mark-up dan lain-lain), jual beli jabatan di pemda (jabatan jabatan strategis eselon), potongan insentif pajak kepada ASN, pemerasan terhadap pengusaha (ekstorsi) maupun penyalahgunaan sumbangan pihak ketiga.
Sumber pemasukan legal dan ilegal tersebut merupakan dampak dari beban pengeluaran rutin yang diperlukan kepala daerah dalam kondisi ekosistem politik yang padat modal, seperti biaya merawat hubungan dengan parpol, pengusaha dan pendukung yang seolah-olah perlu terus dijaga agar tetap tumbuh demi kepentingan politik jangka panjang, biaya memelihara tim sukses dan pembiayaan operasional partai yang menjadi salah satu iuran yang diambil dari kepala daerah, biaya menjaga relasi dengan tokoh masyarakat dan pejabat baik pusat dan daerah, dan yang tidak kalah penting adalah biaya persiapan untuk maju pilkada kembali, entah itu sebagai petahana atau pada level yang lebih tinggi.
Data dari Kemendagri terlihat bahwa persoalan korupsi kepala daerah menjadi persoalan mendasar dalam kepemimpinan hasil dari demokrasi yang dihasilkan dari iklim kontestasi yang ada, yakni sebanyak 465 kasus hukum menjerat kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2005–2024. Dari jumlah kasus tersebut terdapat 406 kepala daerah terjerat kasus korupsi, 11 kasus pemalsuan dokumen, 9 kasus penganiayaan, 9 kasus penipuan, 7 kasus penyalahgunaan izin, 4 kasus pencemaran nama baik, 2 kasus penyalahgunaan narkoba, 2 kasus penghinaan, 2 kasus perjudian, 2 kasus KDRT, 1 kasus perjalanan luar negeri tanpa izin, dan 1 kasus penghinaan agama.
Dari 406 kasus korupsi tersebut mayoritas kasus dipimpin oleh bupati sebanyak 229 kasus (51,6 persen), wali kota sebanyak 70 kasus (17,1 persen), wakil bupati sebanyak 48 kasus (11,8 persen), gubernur sebanyak 37 kasus (9,1 persen), wakil wali kota sebanyak 15 kasus (3,7 persen), dan wakil gubernur dengan 7 kasus (1,73 persen). Data tersebut membuat wajah demokrasi electoral masih menyisakan banyak pekerjaan rumah baik dalam hal proses penyelenggaraan (electoral process) dan sistem pemilihan (election system).
Fenomena Calon Tunggal
Hari hari ini kita disibukkan dengan dinamika politik lokal yang makin menunjukkan anomalinya, kemunculan calon tunggal di beberapa daerah dianggap cukup meresahkan pelaksanaan demokrasi lokal kita. Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan terdapat 37 daerah melaksanakan pilkada dengan calon tunggal dengan sebaran wilayah 1 provinsi, 31 kabupaten, dan 5 kota. Lantas kita perlu bertanya apakah ini merupakan fenomena atau justru menjadi gejala dinamika politik lokal yang makin elitis?
Ruang kandidasi menjadi ruang gelap yang menciptakan pilkada abal-abal, seolah-olah kehendak publik tidak dianggap menjadi satu pertimbangan utama. Terdapat beberapa daerah di Indonesia di mana terdapat kandidat dengan elektabilitas yang tinggi namun justru dieliminasi oleh elite dalam ruang kandidasi. Hal ini terjadi anomali di mana basis utama dukungan biasanya disandarkan pada elektabilitas calon namun yang terjadi justru sebaliknya.
Faktor regulasi dan elektabilitas yang memainkan peran cukup penting pada konfigurasi calon tunggal di daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa barrier to entry sudah diturunkan melalui putusan MK, namun hal itu hanya memberikan ambang batas bawah atau batas minimum syarat dalam kontestasi, belum terdapat ambang batas maksimum atas koalisi. Dengan demikian, peluang untuk untuk borong partai masih tetap terbuka. Hal ini yang kemudian menghilangkan makna persaingan dalam demokrasi.
Studi yang dilakukan Ed.Apinall dan Adianus Hendrawan menunjukkan makin dekat jadwal pilkada dan pilpres makin besar pola koalisi akan dipengaruhi oleh koalisi pilpres yang lebih dahulu terbentuk. Hal ini terbukti di beberapa wilayah strategis di Indonesia. Selain itu, pola rekomendasi yang dilakukan oleh partai politik sangat sentralistik di mana DPP memainkan peran dominan pada kandidasi, meskipun terdapat usulan dari DPD. Masih terlihat di beberapa wilayah antara aspirasi DPD dan keluaran DPP tidak linier dengan kehendak publik dan aspirasi di daerah.
Terjadi keterputusan keterhubungan (broken linkage) antara aspirasi publik dengan keluaran yang dihasilkan oleh partai politik tersebut membuat politik mengerucut pada demokrasi di level elite. Selain itu, pragmatisme partai menjadi satu kondisi tersendiri yang membuat pilkada calon tunggal mewarnai di Indonesia. Jika bisa masuk lebih jauh kita bisa melihat bagaimana terdapat tukar guling kekuasaan pada basis-basis tertentu, terdapat partai politik yang ingin mengamankan basis utama demi menjaga posisi tawar pada menuju 2029. Dengan menjaga daerah-daerah strategis dari basis partai tersebut tentu membuka peluang hegemoni partai tetap terjaga, di satu sisi pilihan yang diambil adalah dengan melepas satu wilayah dan fokus pada wilayah-wilayah dengan calon incumbent dengan elektabilitas yang dianggap tinggi.
Meskipun putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 yang terbit pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu seolah-olah menjadi angin segar, namun keluarnya putusan tersebut dianggap masih terlalu dekat dengan batas waktu pencalonan pada tanggal 27-29 Agustus. Di mana mayoritas rekomendasi partai dari DPP sudah keluar sebelum putusan MK tersebut keluar sehingga tidak banyak memengaruhi konfigurasi politik di daerah.
Kemudian kompromi di tingkat elite nasional dan daerah yang bersama-sama mengusung calon tertentu membuat konfigurasi makin kuat pada calon tunggal serta ditambah lagi dengan mayoritas incumbent yang berkontestasi tentu membuat partai politik akan berpikir ulang untuk mengusung pasangan calon. Hal ini disebabkan persoalan anggaran yang akan dikeluarkan dalam kontestasi yang menjadi pertimbangan bagi parpol sebelum mengusung calon yang kemudian melawan calon secara elektabilitas cukup kuat.
Biaya Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia
Mahalnya ongkos penyelenggaran pilkada menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama dan capaian substansial yang perlu dicapai demi memastikan manfaat penyelenggaraan pilkada. Sejak 2005 hingga 2024 negara sudah mengalokasikan Rp89,67 triliun yang jika dirinci pada 2005 diselenggarakan di 269 daerah (Rp7,09 triliun), tahun 2007 diselenggarakan di 101 daerah (Rp5,96 triliun), tahun 2008 digelar di 171 daerah (Rp15,16 triliun), tahun 2020 digelar di 270 daerah (Rp20,46 triliun), dan tahun 2024 digelar di 545 daerah dengan biaya mencapai Rp41 triliun).
Pertanyaan pada judul opini perlu kita renungkan dan perjuangkan bersama, yakni pilkada akan hasilkan apa? Sejatinya dengan anggaran sebesar itu, pilkada berkorelasi dengan tujuan demokrasi yang ingin dicapai, yakni pilkada yang bermakna, pilkada yang menyejahterakan, dan pilkada yang meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial. Semua ini perlu diperjuangkan dan dikawal bersama.
Pasca-1998, kita semua berharap ada perubahan signifikan pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Sejak 2005 hingga 2020 yang lalu sebagai pelaksanaan terakhir pemilihan kepala daerah, sebagian ilmuwan berpendapat otonomi daerah masih jauh panggang dari api, pilkada dianggap masih menyisakan begitu banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Persoalan korupsi, munculnya oligarki di tingkat lokal yang biasa di sebut raja-raja kecil di daerah, pelayanan publik masih belum optimal hingga upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang sejak awal reformasi menjadi cita-cita bersama. (*)
| Arsitek Transformasi: Kepemimpinan Transformatif dalam Membangun Ekosistem Digital Bangka Belitung |

|
|---|
| Sindeng dari Bangka Selatan Menasional |

|
|---|
| Mengedukasi Pesantren |

|
|---|
| Ironi SDM Bangka Belitung: Kaya Sumber Daya, Krisis Daya Saing |

|
|---|
| Menjembatani Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pertambangan Timah di Bangka Belitung |

|
|---|









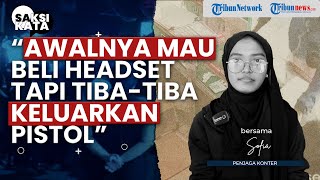




Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.