Tribunners
Memaknai Ulang Sumpah Pemuda: Mewujudkan Inklusivitas Kebijakan Publik Berbasis Pemuda
Indonesia digdaya dimulai dari pemberdayaan pemudanya di setiap daerah, di setiap sudut negeri ini.
Diskursus tentang inklusivitas kebijakan pemuda harus dimulai dengan membaca ulang konsep demokrasi itu sendiri. Terlalu lama kita terjebak pada demokrasi prosedural yang mengukur kualitas demokrasi dari ada tidaknya pemilu atau jumlah forum konsultasi publik. Seperti yang dikritik Amartya Sen, demokrasi sejati harus bersifat substantif: mampu menghasilkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan riil bagi seluruh warga.
Dalam kerangka demokrasi substantif, inklusivitas kebijakan pemuda diukur dari seberapa besar pengaruh mereka dalam membentuk agenda kebijakan dan seberapa responsif sistem terhadap aspirasi mereka. Jürgen Habermas menekankan pentingnya "ruang publik" yang inklusif, rasional, dan setara—ruang di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan memengaruhi kebijakan, terlepas dari usia atau status sosial.
Realitas di banyak daerah Indonesia menunjukkan bahwa ruang publik yang ada belum sepenuhnya Habermasian. Forum-forum kebijakan masih didominasi oleh aktor-aktor tradisional: kepala desa,
tokoh adat, pengusaha lokal, dan birokrat senior. Ketika pemuda masuk ke ruang ini, mereka sering kali tidak dianggap sebagai pembicara yang setara. Usulan mereka harus melalui "filter" yang lebih ketat dibanding usulan dari tokoh senior. Bahasa dan logika yang mereka gunakan, yang mungkin lebih teknis atau dipengaruhi oleh wacana global, sering kali dianggap "tidak membumi" atau "terlalu idealis". Ini adalah bentuk eksklusi simbolik yang menggerus substansi demokrasi.
Untuk mewujudkan demokrasi substantif berbasis pemuda, diperlukan transformasi mendasar dalam cara kita memahami dan mempraktikkan partisipasi. John Gaventa membedakan tiga bentuk ruang partisipasi: ruang tertutup, ruang yang diundang, dan ruang yang diciptakan. Selama ini, partisipasi pemuda lebih banyak terjadi di "invited spaces"—mereka datang karena diundang, berbicara dalam agenda yang sudah ditentukan, dan hasilnya sering tidak mengikat. Yang dibutuhkan adalah "claimed spaces", di mana pemuda sendiri yang menciptakan ruang partisipasi, menentukan agenda, dan memiliki kekuatan untuk memaksa sistem merespons.
Memetakan ulang kebijakan: dari youth-targeted ke youth-led
Salah satu kesalahan fundamental dalam pendekatan kebijakan pemuda selama ini adalah asumsi bahwa pemuda adalah objek atau target kebijakan, bukan subjek atau aktor kebijakan. Sebagian besar program kepemudaan bersifat "youth-targeted"—program yang dirancang untuk pemuda, tetapi bukan oleh atau bersama pemuda. Paradigma ini menciptakan ketergantungan dan mengabaikan agensi pemuda sebagai agen perubahan yang aktif.
Yang dibutuhkan adalah transformasi paradigma dari "youth-targeted" ke "youth-led". Konsep ini menekankan bahwa pemuda harus menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengimplementasikan program, dan mengevaluasi dampaknya. Dalam kerangka ini, peran pemerintah dan pihak lain adalah sebagai fasilitator dan enabler, bukan sebagai perancang tunggal.
Transformasi paradigma ini memerlukan perubahan pada tiga level. Pertama, level kebijakan: harus ada regulasi yang secara eksplisit mengakui dan melindungi hak pemuda untuk berpartisipasi dalam seluruh siklus kebijakan. Kedua, level institusional: harus ada mekanisme dan struktur yang memfasilitasi kepemimpinan pemuda, seperti dewan pemuda dengan kewenangan anggaran dan rekomendasi yang mengikat. Ketiga, level kultural: harus ada perubahan mindset bahwa pemuda adalah aset, bukan beban; mereka adalah solusi, bukan masalah; mereka adalah pemimpin masa kini, bukan hanya masa depan.
Ekonomi politik kepemudaan
Diskusi tentang inklusivitas kebijakan pemuda tidak bisa dipisahkan dari realitas ekonomi politik yang lebih luas. Nancy Fraser, dalam teorinya tentang keadilan, menjelaskan bahwa keadilan sosial memerlukan tiga dimensi: redistribusi (keadilan ekonomi), rekognisi (keadilan kultural), dan representasi (keadilan politik). Ketiga dimensi ini saling terkait dan harus dipenuhi secara simultan.
Di Indonesia, pemuda sering berhadapan dengan ketidakadilan di ketiga dimensi itu . Dari sisi redistribusi, data menunjukkan tingginya angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur di kalangan pemuda. Keterbatasan lapangan kerja formal memaksa banyak pemuda bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ekonomi ini membuat mereka tidak memiliki waktu, energi, dan sumber daya untuk terlibat dalam partisipasi politik yang bermakna. Mereka terlalu sibuk bertahan hidup untuk memikirkan kebijakan publik.
Dari sisi rekognisi, pemuda sering mengalami misrecognition—mereka tidak diakui sebagai kontributor yang bernilai bagi masyarakat. Status sosial pemuda yang rendah, terutama yang belum menikah atau belum memiliki pekerjaan formal, membuat mereka tidak dianggap memiliki legitimasi untuk berbicara tentang urusan publik. Ini adalah bentuk ketidakadilan kultural yang mengakar dalam struktur sosial.
Dari sisi representasi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pemuda mengalami ekslusi dari ruang-ruang pengambilan keputusan. Mereka tidak memiliki akses yang setara ke arena politik dan tidak memiliki kekuatan untuk membentuk aturan main dalam partisipasi politik itu sendiri. Fraser menyebut ini sebagai "misframing"—ketika kelompok tertentu tidak diakui sebagai subjek keadilan yang sah.
Implikasi dari kerangka Fraser ini adalah bahwa inklusivitas kebijakan pemuda tidak bisa hanya fokus pada dimensi representasi politik. Harus ada upaya simultan untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, akses pembiayaan untuk wirausaha muda, dan jaminan sosial yang memadai.
Membangun ekosistem inklusivitas













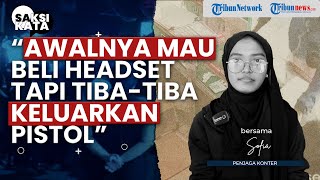





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.