Tribunners
Pilkada 2024: Demokrasi atau Kapitalisasi Politik?
Dalam konteks pilkada, kapitalisasi politik terlihat pada fenomena biaya politik yang sangat tinggi
Oleh: Tian Rahmat, S.Fil. - Alumnus Filsafat IFTK Ledalero, Flores/Pemerhati Isu-isu Strategis
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) adalah salah satu pilar demokrasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Namun, dalam konteks politik modern Indonesia, pertanyaan yang sering mencuat adalah apakah pilkada benar-benar mencerminkan semangat demokrasi, atau sekadar menjadi panggung kapitalisasi politik? Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sinis, tetapi hemat saya relevan di tengah fenomena politik uang, kekuatan oligarki, serta keterlibatan elite bisnis dalam mendanai kampanye.
Demokrasi dan Kapitalisasi Politik: Definisi yang Kabur
Dalam teori politik, demokrasi secara ideal merupakan sistem di mana setiap suara memiliki nilai yang sama, dan pemimpin terpilih adalah representasi nyata dari aspirasi rakyat (Dahl, 1971). Namun, di balik idealisme ini, pilkada kerap kali berhadapan dengan realitas yang rumit. Kapitalisasi politik atau “political capitalism” adalah istilah yang mencerminkan kondisi ketika uang dan modal menjadi instrumen utama untuk meraih kekuasaan (Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail, 2012). Dalam konteks pilkada, kapitalisasi politik terlihat pada fenomena biaya politik yang sangat tinggi, yang tidak jarang memaksa kandidat mencari dukungan finansial dari elite bisnis.
Apakah masyarakat benar-benar berkuasa dalam proses ini, atau justru terjebak dalam skenario politik yang dikendalikan oleh pemilik modal?
Fenomena “Money Politics” dalam Pilkada
Praktik “politik uang” atau money politics telah menjadi salah satu hambatan utama yang mengancam integritas pilkada di Indonesia. Praktik ini menciptakan ketidaksetaraan antara kandidat, di mana kandidat dengan dukungan finansial yang besar memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan pemilihan.
Menurut laporan Bawaslu pada Pilkada 2020, hampir 40 persen kasus pelanggaran yang dilaporkan adalah terkait praktik politik uang (Bawaslu, 2020). Sementara itu, di sisi masyarakat, pemilih sering kali menganggap bahwa menerima uang adalah “keuntungan” dari momen pemilihan, tanpa menyadari bahwa tindakan ini dapat mencederai integritas demokrasi jangka panjang.
Politik uang dalam pilkada juga memicu isu moral dan etika. Banyak pihak, termasuk pakar demokrasi dan aktivis antikorupsi, menilai bahwa praktik ini bukan hanya menghancurkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menguatkan budaya korupsi di Indonesia. Chomsky dalam Manufacturing Consent (1988) menyebutkan bahwa kontrol elite terhadap proses demokrasi pada akhirnya akan menciptakan manipulasi yang menguntungkan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan realitas pilkada di banyak daerah di Indonesia, di mana kandidat sering kali menggunakan kekuatan finansial untuk membeli dukungan, dan masyarakat yang termarginalkan secara ekonomi justru menjadi target empuk.
Peran Oligarki dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah
Oligarki, atau kelompok kecil elite yang memiliki kekuatan besar dalam ekonomi dan politik, juga menjadi aktor penting dalam kapitalisasi pilkada. Winters (2011), dalam bukunya Oligarchy, mengemukakan bahwa oligarki di Indonesia tumbuh subur karena adanya saling ketergantungan antara elite politik dan elite bisnis. Dalam konteks pilkada, oligarki memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya pemilihan melalui pendanaan dan pengaruh. Akibatnya, demokrasi lokal bukan lagi milik rakyat, tetapi dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan finansial. Dengan kata lain, pilkada berubah menjadi kompetisi yang bukan hanya soal gagasan dan visi, tetapi lebih kepada siapa yang memiliki dana lebih besar untuk menjalankan kampanye.
Politik Identitas sebagai Instrumen Kapitalisasi
Di luar fenomena politik uang dan oligarki, isu politik identitas juga menjadi instrumen kapitalisasi yang sering kali disalahgunakan dalam pilkada. Dalam beberapa kasus, kandidat cenderung menggunakan latar belakang etnis, agama, atau bahkan sentimen lokal untuk menggalang dukungan.
Fenomena ini merusak demokrasi karena pemilih akhirnya tidak memilih berdasarkan kapasitas dan visi, tetapi karena identitas yang diusung kandidat. Hal ini mengingatkan kita pada pandangan Pierre Bourdieu dalam Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1984), yang menyatakan bahwa praktik sosial sering kali mencerminkan dominasi simbolis dari kelompok tertentu. Politik identitas dalam pilkada tidak hanya memperkuat segregasi sosial, tetapi juga menciptakan polarisasi yang berbahaya bagi kohesi sosial.
Menghadirkan Pilkada yang Demokratis dan Berintegritas
Meski berbagai tantangan di atas tampak kompleks, bukan berarti harapan untuk mewujudkan pilkada yang demokratis telah hilang. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh guna meminimalisasi kapitalisasi politik dalam pilkada. Pertama, peran masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan menjadi sangat penting. Partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi nonpemerintah dan media independen dapat menjadi penyeimbang kekuatan modal yang menguasai politik lokal.
| Arsitek Transformasi: Kepemimpinan Transformatif dalam Membangun Ekosistem Digital Bangka Belitung |

|
|---|
| Sindeng dari Bangka Selatan Menasional |

|
|---|
| Mengedukasi Pesantren |

|
|---|
| Ironi SDM Bangka Belitung: Kaya Sumber Daya, Krisis Daya Saing |

|
|---|
| Menjembatani Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pertambangan Timah di Bangka Belitung |

|
|---|
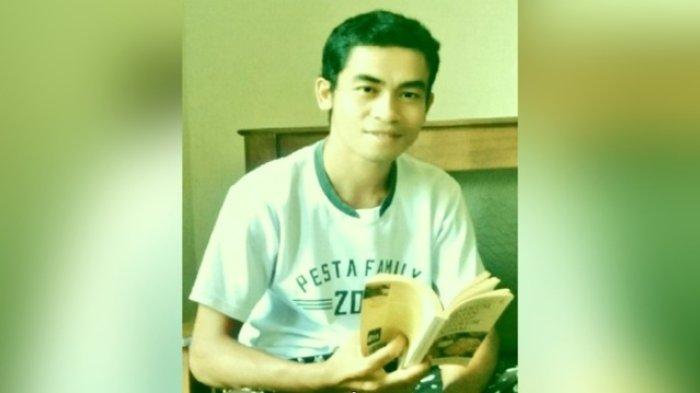













Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.